

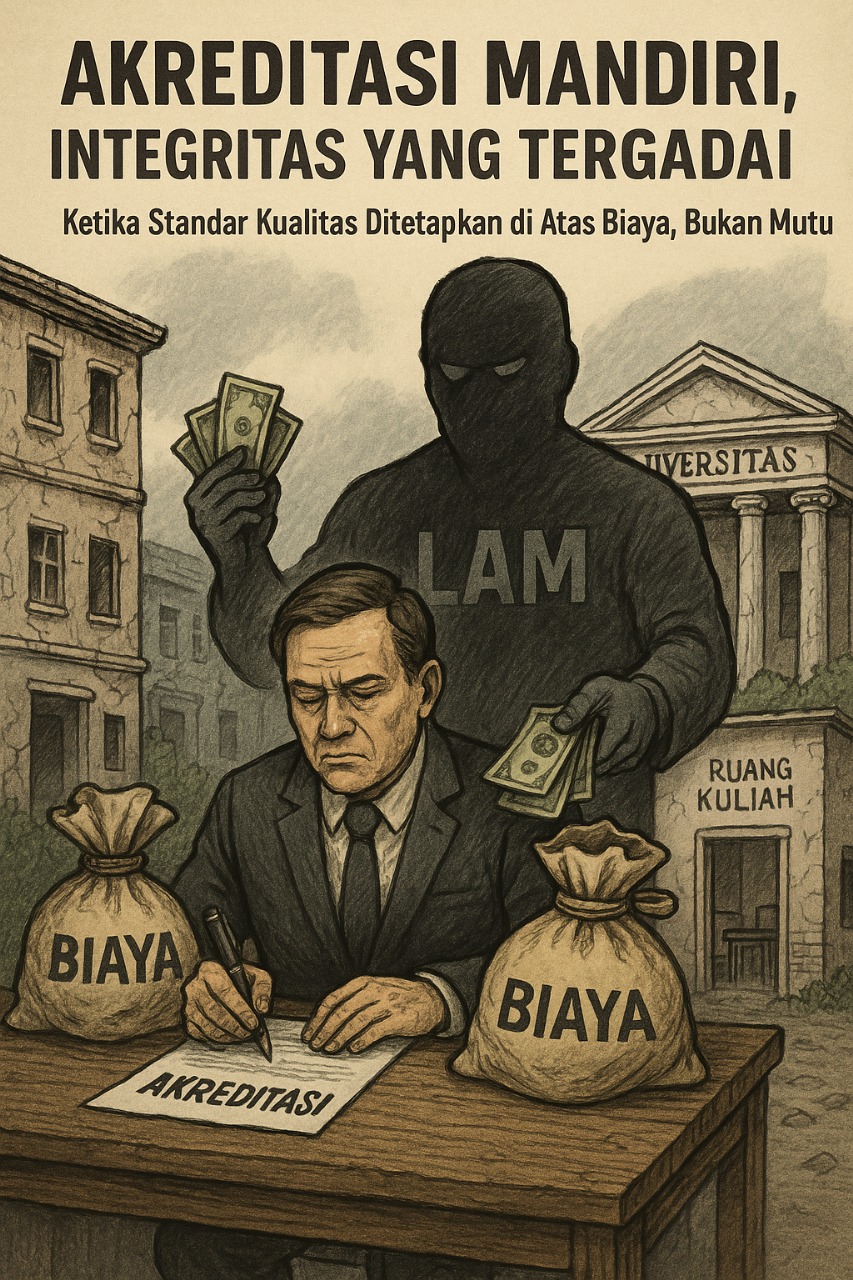
Di atas kertas, kita diajarkan bahwa
pendidikan adalah jalan menuju peradaban. Bahwa universitas adalah benteng
terakhir akal sehat. Bahwa lembaga akreditasi hadir untuk menjaga mutu
pendidikan agar tak tergelincir menjadi ladang komersialisasi. Namun di negeri
ini, kertas tak selalu menjelma kenyataan. Tulisan-tulisan indah tentang
kualitas sering kali terhapus oleh tinta-tinta transaksional. Dan salah satu
wajah dari paradoks ini adalah Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sebuah entitas
yang katanya independen, tapi dalam praktiknya tak ubahnya menjadi
bayang-bayang dari lembaga yang dinilainya sendiri.
LAM, yang seharusnya berdiri di atas
prinsip obyektivitas, kini dipertanyakan independensinya secara terbuka.
Alih-alih menjadi lembaga penjamin mutu, ia kerap dianggap justru menjadi
gerbang legitimasi palsu bagi kampus-kampus yang sejatinya belum pantas
mengklaim diri sebagai institusi pendidikan bermutu. Pertanyaannya: apakah LAM
adalah pagar kualitas atau justru pintu belakang yang bisa dibuka siapa saja asal
membawa cukup banyak uang dan koneksi?
Sungguh ironis ketika kita
menyaksikan kenyataan pahit bahwa kampus-kampus yang bahkan belum memiliki
gedung sendiri, yang hanya menyewa dua lantai di ruko sempit pinggir kota,
justru menyabet predikat “Baik Sekali” dalam akreditasi. Apa makna dari “baik
sekali” jika ruang dosen tak ada, laboratorium hanya sebatas nama, dan ruang
kelas sempit yang serupa gudang lebih layak disebut tempat bimbingan belajar
ketimbang perguruan tinggi? Ini bukan sekadar soal estetika infrastruktur ini
tentang keseriusan dalam membangun lingkungan akademik yang layak dan
manusiawi.
Tapi jangan heran, sebab dalam logika
akreditasi yang kini berkembang, bukan mutu yang diukur, melainkan kepatuhan
terhadap format dokumen. Prosedur kaku, checklist kering, dan pengisian borang
yang lebih mirip ujian administratif ketimbang proses penilaian substansi. Maka
tak salah jika para pengelola kampus lebih sibuk menyiapkan dokumen ketimbang
memperbaiki mutu. Sebab mereka tahu, dokumen bisa direkayasa, tapi memperbaiki
sistem membutuhkan waktu dan integritas dua hal yang kian langka di tengah
industri pendidikan kita yang semakin pragmatis.
Salah satu alat kekuasaan LAM yang
paling kontroversial adalah pemaksaan terhadap kurikulum berbasis OBE (Outcome
Based Education). Ide OBE memang tak keliru; di negara-negara maju ia menjadi
instrumen penting untuk menyelaraskan capaian pembelajaran dengan kebutuhan
dunia nyata. Tapi penerapan yang serampangan dan memaksa di Indonesia, tanpa
pemahaman mendalam dan kesiapan sumber daya, justru menjadikan OBE sebagai
jargon kosong.
Di lapangan, fakta yang menyakitkan
adalah: pengakuan atas kurikulum berbasis OBE justru tergantung pada siapa yang
menjadi narasumber pelatihannya. Jika narasumber berasal dari LAM, meskipun materinya
dangkal dan implementasinya setengah hati, kurikulum itu tiba-tiba mendapat cap
“OBE compliant.” Sebaliknya, jika perguruan tinggi merancang sendiri
kurikulumnya dengan susah payah, mendatangkan pakar-pakar non-LAM, menyusun
struktur capaian pembelajaran dengan serius, itu tak cukup. Kenapa? Karena tak
ada stempel dari “orang dalam.” Ini bukan lagi persoalan ilmiah ini sudah masuk
wilayah patronase dan gengsi kelembagaan. Di sinilah wajah pendidikan kita
dipermalukan di depan etika akademik.
Lebih menyakitkan lagi adalah fakta
bahwa akreditasi ini dibayar mahal oleh perguruan tinggi itu sendiri. Ya,
dibayar. Bukan hanya biaya administrasi, tetapi juga seluruh operasional
visitasi, akomodasi asesor, bahkan mungkin dalam beberapa kasus, ada “kebiasaan”
di balik layar yang seolah menjadi rahasia umum: pemberian service yang
“berlebihan” agar suasana penilaian menjadi lebih “ramah.” Biaya akreditasi
yang membengkak, mulai dari Rp40 juta hingga Rp75 juta per program studi, bukan
hanya beban finansial yang berat bagi kampus-kampus kecil, tapi juga
menciptakan relasi timpang antara yang menilai dan yang dinilai.
Inilah ironi kita: dalam sistem yang
katanya independen, justru kampuslah yang membiayai seluruh proses akreditasi.
Bukankah ini mirip sidang pengadilan di mana terdakwa membiayai hakim? Lantas
bagaimana kita bisa yakin bahwa hasil penilaiannya objektif? Di sini,
pertanyaan moral menganga lebar: apakah asesor LAM bisa benar-benar menilai
dengan hati nurani, jika ia tahu bahwa rektor, dekan, dan ketua prodi sudah
bersusah payah mengeluarkan dana besar untuk “menjamu” mereka?
Tak sedikit cerita dari balik layar
visitasi yang meresahkan. Asesor yang terlihat enggan memberi penilaian
objektif karena tak tega menyakiti pihak kampus yang telah bersusah payah
menyambut mereka. Asesor yang menutup mata pada kelemahan-kelemahan struktural
karena merasa berhutang budi atas perlakuan yang nyaman selama visitasi. Kampus
yang menyembunyikan kekurangan dengan “menyulap” dokumen dan merias tempat
visitasi dalam waktu semalam. Semua menjadi drama akreditasi yang dikemas rapi
demi satu tujuan: nilai baik.
Pemerintah dan Kementerian Pendidikan
pun tak bisa cuci tangan dari kegaduhan ini. Sebab mereka justru yang membuka
jalan bagi hadirnya LAM, menyerahkan sepenuhnya urusan mutu pendidikan tinggi
kepada entitas di luar negara. Di atas nama otonomi, negara melepaskan tanggung
jawabnya terhadap mutu. Tapi yang tak disadari adalah: otonomi tanpa pengawasan
yang sehat hanya akan melahirkan lembaga yang merasa tak tersentuh hukum dan
etika.
Maka jangan heran jika masyarakat
perlahan mulai apatis terhadap makna akreditasi. Jika seorang lulusan dari
kampus “akreditasi unggul” ternyata tak mampu menulis surat lamaran kerja
dengan baik, siapa yang harus disalahkan? Jika program studi dengan predikat
“baik sekali” ternyata tak memiliki dosen tetap yang cukup, apa arti semua
simbol kualitas itu? Akreditasi yang seharusnya menjadi refleksi mutu telah
berubah menjadi kosmetik kelembagaan.
Kita perlu jujur dan berani
mengatakan bahwa sistem ini sedang sakit. Bahwa LAM dalam praktiknya tidak
sedang menjaga kualitas, tapi justru menjadi bagian dari masalah. Pendidikan
tinggi kita bukan hanya butuh evaluasi, tapi reformasi menyeluruh. Reformasi
yang menyasar ke jantung persoalan: transparansi, integritas, profesionalisme.
Pendidikan tidak boleh disandera oleh
birokrasi boros dan lembaga akreditasi yang menjelma menjadi lembaga jasa
legalisasi mutu. Tidak boleh ada lagi tempat bagi “akreditasi semu” yang
dibangun di atas relasi transaksional. Pendidikan harus kembali ke marwahnya:
sebagai instrumen pembebasan, bukan legitimasi palsu.
Kini saatnya pemerintah turun tangan.
Negara tidak boleh tinggal diam melihat lembaga yang mengklaim diri sebagai
penjaga mutu justru terjebak dalam transaksi mutu semu. LAM harus diaudit
secara menyeluruh bukan hanya audit finansial, tapi juga audit etik dan
akademik. Jika tidak, maka sesungguhnya negara sedang membiarkan sistem
pendidikan tingginya digerogoti dari dalam, dengan legalitas yang semu dan
kualitas yang tak pernah menjadi prioritas.
Dan kepada masyarakat, para orang
tua, mahasiswa, dan para akademisi muda: janganlah tertipu oleh label
akreditasi di atas kertas. Lihatlah isi kampus, bukan sampulnya. Tanyakan:
apakah dosennya berkualitas? Apakah ruang belajarnya layak? Apakah mahasiswa
dibentuk untuk berpikir atau sekadar dikondisikan untuk mengejar IPK?
Jika kita terus membiarkan
lembaga-lembaga seperti LAM berjalan tanpa koreksi, tanpa kritik, dan tanpa
reformasi, maka yang terjadi bukan hanya degradasi pendidikan. Tapi pembusukan
sistem dari dalam. Dan pada akhirnya, kita hanya akan mewarisi generasi yang
terdidik secara administratif tapi kosong secara intelektual.
LAM bukan lembaga dewa. Ia harus diawasi. Ia harus diaudit. Ia harus dikritik. Karena hanya dengan itulah, pendidikan tinggi Indonesia bisa bangkit dari koma panjangnya. Dan hanya dengan itulah, bangsa ini bisa berharap pada generasi yang benar-benar terdidik bukan sekadar terakreditasi.
Penulis: Dr. Hengki Tamando Sihotang, M.Kom - Peneliti IOCSCIENCE
Viewers

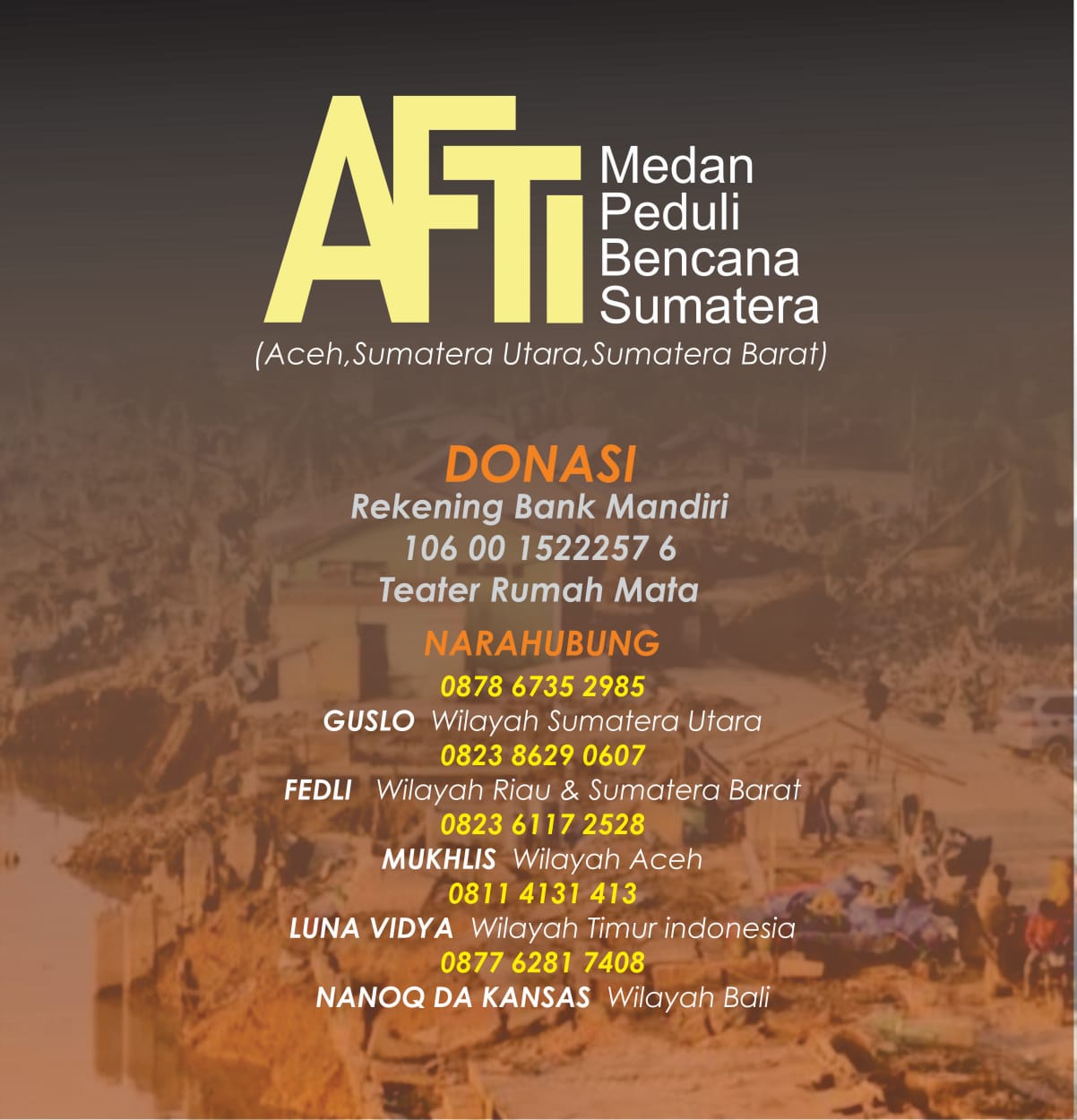
Jika memang benar narasi ini, harus dibenahi sistem dan mekanisme pendidikan di Indonesia khususnya dalam hal akreditasi.
avg
02-07-2025 20:07